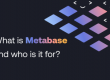Penetapan status darurat militer di Korea Selatan oleh Presiden Yoon Suk Yeol pada Selasa (3/12) malam waktu setempat menuai amarah publik di negara tersebut.
Sebab, ada banyak warga di Negeri Ginseng yang menolak status ini.
Mereka melakukan demo besar-besaran di depan Gedung Majelis Nasional Korsel guna mendesak Yoon mundur dari kursi presiden dan mendesak militer Korsel untuk menangkapnya.
“Tangkap Yoon Suk Yeol,” teriak para demonstran, dikutip dari New York Times.
Di tempat lain, tepatnya, di tepi Lapangan Gwanghwamun, pusat kota Seoul, juga terjadi hal serupa. Di sana, ada beberapa orang memegang poster yang menyerukan pengunduran diri Presiden Yoon.
Imbas protes ini, Presiden Yoon akhirnya memutuskan untuk mencabut status darurat militer di Korsel pada Rabu (4/12) pagi waktu setempat. Pencabutan status darurat militer itu dilakukan setelah Yoon mengumpulkan anggota kabinetnya dan menyetujui desakan Majelis Nasional melalui voting untuk membatalkan darurat militer.
Lantas, mengapa warga Korsel marah dan menolak status darurat militer yang sempat ditetapkan Presiden Yoon?
Faktor sejarah kelam
Pengamat hubungan internasional Universitas Diponegoro, Aniello Ello Iannone, mengatakan, penolakan darurat militer oleh oleh warga Korsel disebabkan sejarah masa lalu di negara tersebut.
Pada 1980-an, rezim otoriter Korsel di bawah tampuk kepemimpinan Chun Doo Hwan juga pernah menetapkan status darurat militer di tengah ketegangan mereka dengan Korea Utara. Ini merupakan kali pertama Korsel menetapkan status darurat militer.
Namun, kata Iannone, status darurat militer di Korsel kala itu malah digunakan sebagai alat untuk mengekang kebebasan publik. Dengan kata lain, Korsel menjadikan status darurat militer itu untuk membuat warga tunduk terhadap keputusan pemerintah.
Muak imbas dikekang pemerintah, warga Korsel pun saat itu melakukan pemberontakan di Kota Gwangju. Pemberontakan ini dilakukan untuk mengubah Korsel menjadi negara yang lebih demokratis.
Peristiwa yang dikenal dengan sebutan Pemberontakan Gwangju ini pun menjadi peristiwa sejarah. Sebab, peristiwa pemberontakan ini tercatat telah menewaskan ratusan jiwa.
Kenangan “gelap” inilah yang pada akhirnya menyebabkan trauma mendalam bagi warga Korsel ketika Presiden Yoon menetapkan status darurat militer pada Selasa lalu. Warga Korsel khawatir peristiwa serupa bak tragedi Gwangju terulang kembali di masa kini.
“Selama periode itu [1980-an], darurat militer digunakan sebagai alat untuk menekan gerakan demokrasi dan kebebasan sipil yang berpuncak pada peristiwa seperti pembantaian pemberontakan Gwangju,” jelas Iannone saat dihubungi CNNIndonesia.com pada Rabu (4/12) WIB.
“Kenangan ini telah meninggalkan asosiasi yang langgeng antara darurat militer dengan penindasan daripada keamanan dan membuat setiap penerapan baru sangat tidak populer,” lanjutnya.